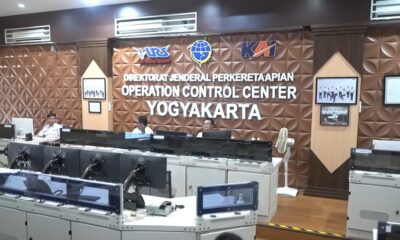Uncategorized
Sampah Elektronik (e-waste): Risiko dan Kebijakannya di Indonesia


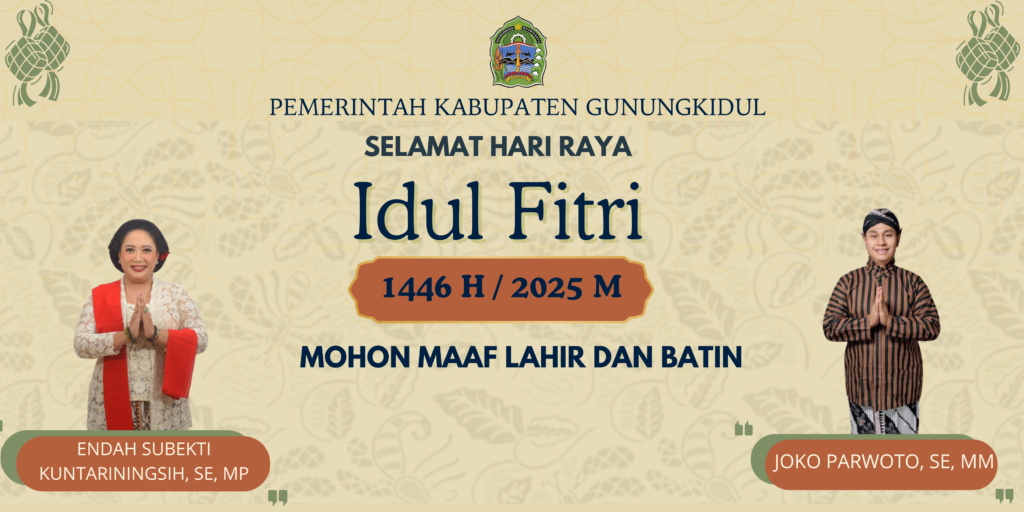



Apa itu sampah elektronik (e-waste)?
Di era digital dan teknologi informasi yang semakin berkembang, penggunaan produk elektronik semakin meningkat. Produsen produk elektronik silih berganti mengeluarkan model terbarunya setiap tahun. Masyarakat kini dengan mudah mengganti produk elektronik lamanya dengan model terbaru. Produk elektronik lama yang sudah tidak terpakai kian bertambah banyak dan pada akhirnya berubah menjadi sampah. Electronic waste atau e-waste adalah jenis sampah atau limbah berupa elektronik atau peralatan listrik termasuk semua komponen, sub-rakitan, dan bahan habis pakai yang merupakan bagian dari peralatan tersebut pada saat peralatan tersebut menjadi limbah (1). E-waste dapat berupa ponsel, laptop, PC, televisi, kulkas, baterai, lampu bohlam, kabel listrik, kipas angin listrik, mesin cuci atau barang elektronik lainnya yang sudah rusak dan tidak dipakai lagi. WHO menyatakan bahwa e-waste merupakan salah satu sampah padat yang pertumbuhannya paling cepat di dunia dan dapat menjadi ancaman bagi kesehatan dan lingkungan jika tidak dibuang dan didaur ulang dengan tepat. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2022 saja diperkirakan 62 juta ton sampah elektronik diproduksi secara global. Hanya 22,3% yang terdokumentasikan telah dikumpulkan dan didaur ulang secara resmi (2).
Menurut PP No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, sampah elektronik dikategorikan sebagai sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Sampah elektronik mengandung bahan berbahaya seperti logam berat pada komponen-komponennya. Logam berat jenis timbal (Pb) terdapat pada PCB (Printed Circuit Board), bola lampu, komponen televisi dan baterai. Sedangkan Kadmium (Cd) terdapat pada detektor inframerah, keping semi-konduktor baterai, dan komponen ponsel. Merkuri (Hg) terdapat pada termostat, sensor, monitor, dan LCD (Liquid-Crystal Display). Unsur nikel dan litium terdapat dalam baterai. Seringkali penanganan sampah elektronik ditangani dengan dibakar. Padahal pembakaran sampah elektronik mengeluarkan asap beracun dan membuat unsur-unsur logam berat seperti timbal, kadmium dan merkuri terhirup oleh manusia (3). Unsur-unsur berbahaya dari sampah elektronik ini dapat terlepas ke lingkungan dan mencemari udara, air, tanah atau bahan pangan.
Lalu bisakah unsur-unsur berbahaya masuk ke tubuh kita? Jawabannya adalah bisa! Unsur-unsur berbahaya dari sampah elektronik tersebut dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui tiga jalur, yaitu konsumsi air, makanan yang terkontaminasi, juga tanah atau debu yang tidak sengaja termakan dan masuk ke dalam tubuh; menghirup gas dan partikel aerosol; dan paparan kulit. Janin dan anak-anak juga dapat terpapar melalui jalur yang unik yaitu konsumsi ASI dan paparan transplasenta dari ibu ke janin yang ada di dalam kandungan (1).
Dampak kesehatan akibat kandungan racun logam berat yang terdapat pada e-waste antara lain gangguan sistem pernapasan akibat menghirup hasil pembakaran e-waste. Dalam jangka panjang, dapat muncul gejala seperti iritasi hidung dan tenggorokan, diikuti batuk, dan sesak napas atau yang lebih serius mengakibatkan asma, biasanya terjadi setelah terpapar pada kadar logam berat yang tinggi. Studi in vivo dan in vitro di Cina menunjukkan bahwa paparan logam berat kronis bisa menyebabkan hipertensi dan penyakit kardiovaskular. Beberapa logam berat diduga menyebabkan neurotoksisitas. Defisit perkembangan saraf anak-anak dari area daur ulang sampah elektronik telah menimbulkan kekhawatiran besar masyarakat di seluruh dunia. Paparan logam berat dalam e-waste juga menyebabkan gangguan sistem imunitas tubuh dan gangguan sistem reproduksi (4).


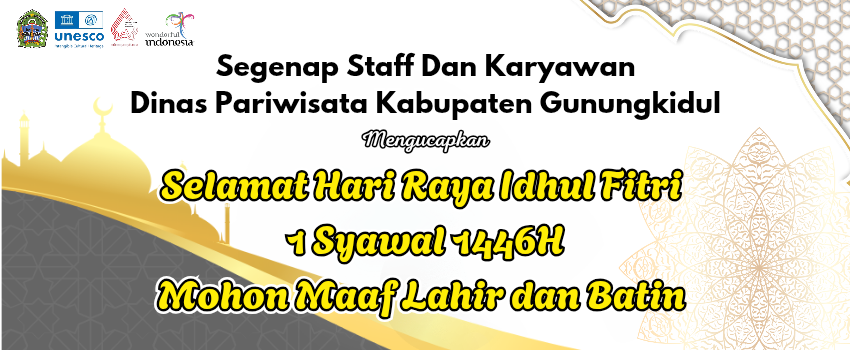


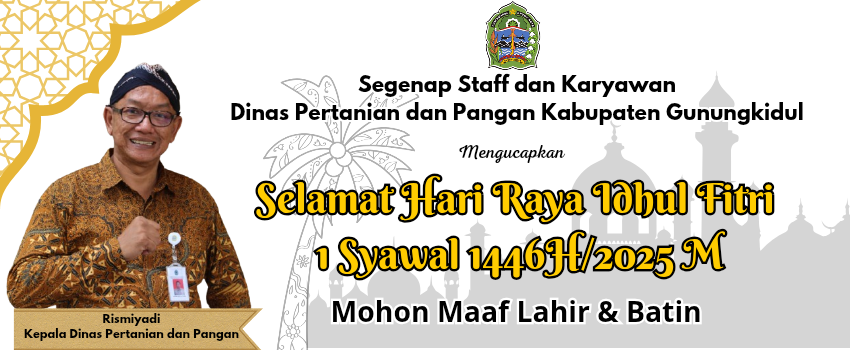

Kebijakan terkait e-waste di Indonesia
Bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi fenomena sampah elektronik yang mau tidak mau akan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi? Pengelolaan sampah elektronik (e-waste) di Indonesia ternyata telah diatur melalui beberapa peraturan berikut:
a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
b. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Mari kita lihat implementasi dari peraturan-peraturan tersebut. Jumlah e-waste di Indonesia setiap tahun semakin meningkat, tetapi berdasarkan berbagai sumber masih banyak permasalahan terkait hal tersebut. Masih sedikit dari e-waste tersebut yang dikelola dengan benar di Indonesia. E-waste sering tercampur dengan sampah biasa dan dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah. E-waste seharusnya dipisahkan dan dikelola oleh pengelola khusus yang memenuhi syarat sebagai pengelola limbah B3. E-waste terkadang berakhir dikelola oleh pengelola sampah informal dan ilegal yang tidak mengetahui pengelolaan sampah B3 dengan baik dan benar sehingga berpotensi untuk menyebabkan pencemaran lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa telah terjadi pencemaran logam berat pada air dan tanah di lingkungan sekitar lokasi daur ulang e-waste informal di Pulau Jawa. Kandungan logam berat yang melebihi batas normal juga ditemukan pada darah dan rambut anak-anak sekitar sekitar lokasi daur ulang e-waste informal dan diduga berpengaruh terhadap kemampuan belajar dan gangguan perilaku anak-anak di lokasi tersebut (5 dan 6).
Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik, pengelolaan e-waste yang dihasilkan rumah tangga diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Pemerintah Daerah (Pemda) harus menyediakan drop box atau dropping point sampah spesifik dan Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik B3 (TPSSS-B3). Tetapi pada prakteknya, masih sulit untuk menemukan dropping point untuk menyalurkan e-waste.
Ancaman pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan akibat sampah elektronik di Indonesia akan semakin meningkat apabila permasalahan terkait e-waste ini tidak segera ditangani. Pemerintah harus segera menertibkan pengelola daur ulang e-waste informal. Tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis daur ulang limbah elektronik ini merupakan bisnis yang cukup meraup keuntungan yang besar bagi sebagian pihak, tetapi potensi bahaya dan dampak negatif dari pengelolaan sampah elektronik yang tidak sesuai akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan EPR (Extended Producer Responsibility) atau take back bagi para produsen produk elektronik. Kebijakan ini mewajibkan para produsen produk elektronik untuk menerima kembali sampah produk elektronik bekas yang mereka produksi utuk nantinya dikelola oleh mereka dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Peran Pemerintah Daerah (Pemda) juga diperlukan untuk mengatasi e-waste ini dengan memperbanyak lokasi dropping point e-waste dan memudahkan masyarakat untuk menyalurkan sampah elektronik yang mereka miliki. Dan yang tidak kalah penting yaitu penyuluhan dan edukasi masyarakat terkait dampak negatif dari pengelolaan e-waste yang tidak benar.
Referensi
1. World Health Organization. (2021). Children and digital dumpsites: e-waste exposure and child health. World Health Organization. https://iris.who.int/handle/10665/341718. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
2. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electronic-waste-(e-waste) diakses tanggal 9 Desember 2024
3. Perkins, D. N., Drisse, M. N. B., Nxele, T., & Sly, P. D. (2014). E-waste: a global hazard. Annals of global health, 80(4), 286-295.
4. Zeng, X., Xu, X., Boezen, H. M., & Huo, X. (2016). Children with health impairments by heavy metals in an e-waste recycling area. Chemosphere, 148, 408-415.
5. Soetrisno, F. N., & Delgado-Saborit, J. M. (2020). Chronic exposure to heavy metals from informal e-waste recycling plants and children’s attention, executive function and academic performance. Science of the Total Environment, 717, 137099.
6. Mansyur, M., Fitriani, D. Y., Prayogo, A., Mutiara, A., Fadhillah, R., Aini, R., … & Bose-O’Reilly, S. (2024). Determinant factors of children’s blood lead levels in Java, Indonesia. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 261, 114426. (Egnes Ekaranti – Mahasiswa S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia)
-

 Pemerintahan2 minggu yang lalu
Pemerintahan2 minggu yang laluBupati Endah Harapkan Tradisi Urbanisasi Mulai Berkurang
-

 Pemerintahan1 minggu yang lalu
Pemerintahan1 minggu yang laluAkhirnya Gunungkidul Akan Kembali Punya Bioskop
-

 Sosial4 minggu yang lalu
Sosial4 minggu yang laluIstri Wakil Bupati Gunungkidul Dilantik Jadi Ketua Tim Penggerak PKK, Ini Hal yang Akan Dilakukan
-

 film2 minggu yang lalu
film2 minggu yang laluDiputar Bertepatan Momen Lebaran, Film Komang Ajak Rayakan Perbedaan
-

 bisnis4 minggu yang lalu
bisnis4 minggu yang laluPT Railink Raih Penghargaan 7th Top Digital Corporate Brand Award 2025
-

 Uncategorized3 minggu yang lalu
Uncategorized3 minggu yang laluMilad ke 12, Sekolah Swasta Ini Telah Raih Ribuan Prestasi
-

 bisnis3 minggu yang lalu
bisnis3 minggu yang laluHadirkan Zona Baru, Suraloka Interactive Zoo Siap Berikan Pengalaman Interaktif dan Edukatif
-

 bisnis3 minggu yang lalu
bisnis3 minggu yang laluSambut Lebaran 2025, KAI Bandara Beri Diskon Tiket dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
-

 Peristiwa3 minggu yang lalu
Peristiwa3 minggu yang laluJelang Lebaran, Polisi Himbau Warga Waspadai Peredaran Uang Palsu
-

 bisnis4 minggu yang lalu
bisnis4 minggu yang laluCatat Kinerja Positif di Tahun 2024, WOM Finance Berhasil Tingkatkan Aset 4,68 Persen
-

 Peristiwa2 minggu yang lalu
Peristiwa2 minggu yang laluKebakaran di Rongkop, Bangunan Rumah Hingga Motor Hangus Terbakar
-

 Pemerintahan2 minggu yang lalu
Pemerintahan2 minggu yang laluPuluhan Sapi di Gunungkidul Mati Diduga Karena Antraks